 |
| Putu Fajar Arcana |
Obituari Mesin Tik Tua Pembuka Cerita
Dalam dunia digital, tak perlu cabut kertas lalu ”dibejek-bejek” karena sebuah kesalahan, tinggal ”delete”.By: Putu Fajar Arcana, jurnalis Kompas 1994-2022,
(Sutradara, Penyair, dan Presidium Alinea)
Saat berhadapan dengan tanjakan yang tinggi, aku harus turun lantaran motor Bang Ojek tak sanggup naik. Matahari sudah berada di ufuk barat. Masih ada sisa cahaya, walau gerimis mulai turun. Apalagi, sepertinya semalam sudah turun hujan. Jalanan tanah yang hanya ditaburi batu-batu besar di beberapa bagian itu cukup licin.
”Itu tas satunya biar taruh di motor,” kata Bang Ojek.
”Tidak. Masih bisa saya pegang,” kataku.
Aku tahu Bang Ojek yang mengaku warga desa di dekat Dusun Pager Gunung itu ingin membantu karena kasihan melihatku tertatih melompat-lompat di atas jalanan yang mulai becek.
Tujuan pertama-tamaku ke dusun itu tak lain mencari sumber penting soal kasus pembunuhan terhadap seorang buruh bernama Marsinah. Hal yang belum terpecahkan, di mana harus menumpang mengetik dan dengan cara apa harus mengirimkannya ke redaksi di Jakarta. Padahal, kasus itu adalah kasus paling mendapat perhatian publik. Sekadar tahu, waktu itu, pengiriman berita hanya bisa dilakukan melalui mesin faksimili di sebuah wartel (warung telekomunikasi).
Baiklah, menggunakan kaki untuk turun ke lapangan menemui narasumber, itu hal pertama. Bahwa jurnalisme harus berhadapan langsung dengan kenyataan. Ia tak boleh diaplikasikan lewat telepon. Mungkin prinsip ini kini terdengar kuno dan ketinggalan zaman. Bagaimana mungkin kecepatan bisa diatasi dengan cara bersusah-susah pergi ke lapangan plus menenteng mesin tik tua segala?
Aku tak mau nyinyir dengan cara kerja ”jurnalistik” belakangan hari, yakni kecepatan adalah hal paling utama. Akurasi adalah perhitungan berikutnya. Jika dalam kecepatan itu terdapat fakta-fakta yang tidak akurat, toh bisa direvisi dalam berita berikutnya. Ya, semudah itu. Tidak akurat atau salah fakta menjadi hal biasa. Tidak perlu merasa bertanggung jawab atas kesalahan itu, sebab masih ada kesempatan berikutnya untuk membuat berita tanpa merasa ada yang salah.
 |
| Penyair Frans Nadjira membaca puisi pada acara peluncuran buku puisinya, Curriculum Vitae, di Taman Budaya Yogyakarta, Minggu (9/9/2007). |
Bahkan, suatu hari aku pernah menyelesaikan menulis lakon monolog di atas gerbong kereta. Waktu itu, Kang Iman Soleh meminta aku menulis sebuah monolog tentang cinta Tanah Air untuk kompetisi anak-anak SMA bernama FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbud Ristek RI.
”Waktunya dua hari saja, Bli,” kata Kang Iman.
”Saya coba…,” kataku yakin.
”Maaf Bli ini dadakan. Baru diberi tahu panitia.”
”Kita lihat nanti hasilnya,” kataku lagi.
Saat Kang Iman menelepon, aku sedang dalam perjalanan berkereta Jakarta-Cirebon untuk satu tugas jurnalistik. Jawaban meyakinkan yang kuberikan kepada Kang Iman rasanya sudah dengan perencanaan yang matang. Perjalanan pergi-pulang Jakarta-Cirebon akan aku gunakan sebaik-baiknya untuk menulis melalui gawai.
Lahirlah kemudian naskah monolog berjudul ”Dokter Jawa”, yang telah dimainkan oleh para siswa SMA dalam ajang FLS2N tahun 2019 di Bandar Lampung. Naskah ini sudah aku satukan dalam buku 9 Monolog Putu Fajar Arcana yang terbit tahun 2022 lalu.
Aku mungkin salah satu dari sedikit penulis yang berhasil mentransformasi kebiasaan. Meski pada awalnya tertatih-tatih, peralihan dari kebiasaan menulis menggunakan mesin tik, perlahan-lahan bisa menggunakan desktop, lalu laptop, dan paling mutakhir menggunakan gawai. Perubahan yang terakhir ibarat ”revolusi jari” karena hanya dibutuhkan dua ibu jari untuk menekan tombol huruf di layar sentuh. Saat menggunakan mesin tik, desktop, dan laptop, masih dibutuhkan 10 jari. Bahkan, sewaktu awal belajar menekan tombol mesin tik, dibutuhkan ”14 jari” alias hanya menggunakan dua telunjuk!
Perbandingan antara mesin tik hadiah Bang Frans dan kebiasaan menulisku kini, yang telah menggunakan hasil kerja teknologi digital, bukanlah dengan maksud menyepelekan masa lalu. Mesin tik bukan pula sekadar romantisme masa lalu, tetapi telah menjadi pembuka cerita, pembuka jalan hidup untuk lebih menghayati sebuah literasi dunia kepenulisan.
Mesin tik tua hadiah Bang Frans kini boleh saja nangkring di salah satu rak bukuku di Jakarta, tetapi ia membawa spirit salah satu guruku dalam menulis. Bang Frans, kami kenal sebagai satu dari dua mahaguru puisi bagi para penyair di Bali. Ia tidak hanya pengembara secara fisik, karena pernah menjadi pelaut dan merantau ke Filipina, tetapi juga pengembara kata-kata yang mumpuni. Banyak hasil pengembaraan kata-kata itu ia tuangkan ke dalam puisi, dan itulah yang menjadi patron penulisan puisi di Bali sampai hari ini. Satu lagi mahaguru yang kumaksud adalah Umbu Landu Paranggi, yang telah wafat tahun 2021.
 |
| Frans Nadjira |
Untuk kali terakhir
kata menjengukmu
karena kata cuma milikku:
"Selamat jalan, batu paras
yang ditatah dengan kapak."
……………………………
Karena kata cuma milikku
Kujenguk kau dengan kata:
"Selamat jalan, batu paras
yang ditatah dengan kapak."
(Frans Nadjira, Selamat Jalan I Gusti Nyoman Lempad)
Penggunaan diksi ”tatah”, ”batu paras”, dan ”kapak” tak hanya berhasil menggambarkan profesi, identitas, dan karakter, tetapi juga menyinergikan karakter keras Bang Frans sebagai orang Bugis dengan karakter pekerja yang dimiliki Lempad. Seniman Bali yang lahir di Bedahulu tahun 1862 itu adalah undagi besar yang penah dimiliki dunia. Lempad tak hanya menatah batu paras dengan ”kapak” saat membuat patung atau membangun pura, tetapi juga melukis dengan kelembutan garis yang luar biasa. Karya-karyanya diakui dunia dan tersimpan di Tropenmuseum (Amsterdam), Rijkmuseum voor Volkenkunde (Leiden), dan Museum fur Volkenkunda Basel (Jerman).
Teknik presentasi dan penggunaan diksi simbolik yang dilakukan Bang Frans sampai hari ini masih menjadi pedoman penulisan puisi para penyair Bali terkini. Pedoman tentu saja tidak serta merta diartikan sebagai copy-paste. Bang Frans adalah api. Ia bisa membakar semangat kepenulisan, bisa pula menjadi penyuluh harapan yang samar-samar di masa depan.
Saat-saat awal memutuskan menjadi jurnalis, Bang Frans berperan besar dalam hidupku. Kami biasa berkumpul di kediamannya di kawasan Biaung, Gianyar. Anak-anak muda seperti Putu Wirata Dwikora, Warih Wisatsana, K Landras Syaelendra, Ketut Naria, Ryanto Rabbah, Mas Ruscita Dewi, Hartanto, Syahruwardi Abbas (alm), dan Tan Lioe Ie seolah berumah di rumah kecil Bang Frans. Saban siang, kami makan seadanya, apa pun yang dimasak oleh Kakak (Unda, istri Bang Frans yang berdarah Minang). Kalau lukisan Bang Frans terjual, biasanya kami makan agak ”mewah”. Setidaknya Kakak memasak masakan Minang paling enak ”di dunia”.
Suatu hari kami putus kerja. Koran di mana kami merintis jalan kewartawanan berhenti terbit pada awal tahun 1990-an, hanya puisi yang jadi modal. Tetapi, media manakah yang bisa saban hari memuat puisi. Masih ada Umbu Landu Paranggi, yang jadi redaktur edisi Minggu di Bali Post. Tetapi, tidak mungkin Umbu memuat puisi kami setiap Minggu, hanya untuk kepentingan sekelompok seniman muda yang ”keras kepala”.
Dengan tulus pasangan Frans Nadjira-Unda setiap hari mengundang kami untuk makan siang di rumahnya. Bahkan, tak jarang kami menginap untuk suatu yang rencana yang agak ”mewah”. Pagi-pagi kami menuju Pantai Biaung yang hanya berjarak 10 menit jalan kaki di selatan perumahan. Di pantai biasanya kami berlatih ”menentang” ombak, merasakan desir angin, mendengar bisikan laut, atau sekadar mengobrol dengan para nelayan lokal.
Sepintas lalu ini pekerjaan sia-sia belaka. Tetapi, itulah yang ditularkan Bang Frans kepada kami. Kami diajar untuk selalu bercakap-cakap di bawah guguran daun, seperti judul kumpulan cerpen yang ditulis Bang Frans tahun 1979 silam. Singkatnya, belajar meresapi setiap aktivitas sehari-hari dengan sepenuh penghayatan.
”Semua akan berguna pada masanya nanti. Kau akan jadi penulis yang sensitif terhadap persoalan kemanusiaan. Sebab, jika tidak dengan begitu untuk apalah kita ini jadi penulis. Begitu, kan?” kata Bang Frans setiap saat.
Kami akhirnya mengerti. Mesin tik yang dihadiahkan Bang Frans tak hanya bermanfaat sebagai alat dan pencetak pengetahuan, tetapi yang lebih penting adalah spirit pendorong kreativitas. Sebagai mesin yang ditemukan pada tahun 1557 oleh Francesco Rampazetto ini, mesin tik adalah akumulasi antara teknologi, pengetahuan, dan kreativitas. Ibaratnya tanpa penemuan ini, sangat mungkin teknologi typing yang diwakili keypad gawai hari ini tidak bakal terciptakan.
Frans adalah mesin tik tua yang terawat baik. Ia tak pernah berkarat dan macet karena tak berfungsi. Sampai akhir hidupnya, Jumat, 12 Januari 2024, Frans tetap berkarya. Sajak-sajaknya dimuat, pada 14 Januari 2024 pada edisi Minggu Harian Nusa Bali.
 |
| Mesin tik hadiah dari Frans Nadjira |
Meski mesin tik itu kini ”terkubur” bersama deru gairah teknologi, yakin ia tetap berdenyar di dalam darahku, darah para penyair yang pernah menimba pengetahuan dari padanya. Frans adalah Bang Frans yang ”meledak-ledak” sekaligus ”mengetikkan” sensivitas kemanusiaan kepada para penyair Indonesia. Ia kami kenang sebagai pencetak huruf-huruf yang dirangkai sendiri oleh para penulis generasi sesudahnya. Ia kami nobatkan sebagai pembuka cerita, pembuka jalan hidup kami, ”anak-anak” muda, yang nyaris kehilangan arah. Selamat jalan Bang. Selamat menulis bait-bait puisi dari surga.
Sumber:
kompas.id➚
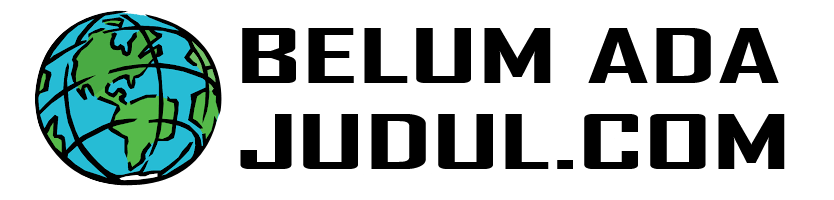
Post a Comment for "Obituari Mesin Tik Tua Pembuka Cerita"